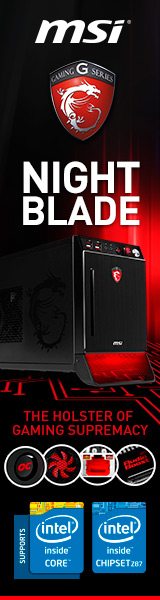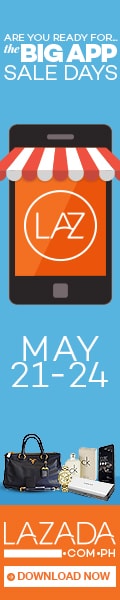Tentang Dienullah Rayes dan Karyanya
Siapa Dienullah Rayes, berikut biodata yang ditulis oleh dirinya sendiri. Dalam analisis puisi sesungguhnya biodata tak penting, tetapi penting jika masih relevan dengan isi puisi yang dibahas.
Dienullah Rayes lahir tahun 1937 di Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa NTB dari pasangan H. Lalu Muhiddin Rayes dan Hj. Ringgi. Ia pernah bertugas sebagai guru SD beberapa tahun (1956-1965). Kemudian beralih tugas ke Kantor Pembinaan Kebudayaan Kabuparen Sumbawa di Sumbawa Besar. Sehubungan dengan reorganisasi, selanjutnya dipindahkan ke Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, dipercaya sebagai Kepala Seksi Kebudayaan sampai pensiun pada tahun 1994.
Aktif menulis sejak tahun 1956 hingga sekarang. Selain menulis puisi juga menulis cerpen, naskah drama, esai budaya (artikel seni dan nonfiksi lainnya), sebagai wartawan. Tulisan-tulisannya tersebut dimuat di media massa pusat dan daerah. Media cetak Malaysia/Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, Singapura pun memuat tulisan/karangannya. Sampai saat ini telah menerbitkan 77 judul buku sastra bersama sastrawan/penyair dalam dan luar negeri. Dari sekian penerbitan tersebut di antaranya 37 buah judul sebagai karya sastra tunggal.
Dalam lomba mencipta puisi yang sifatnya islami “IQRA” tingkat nasional meraih 10 besar puisi terbaik putra tahun 1992. Yayasan Gunungan Magelang menyelenggarakan Lomba Cipta Puisi Nasional Borobudur Award 1997. Dia berhasil merebut 10 puisi nominasi. Sebagai sastrawan berprestasi melalui Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) memperoleh anugerah ibadah haji ke tanah suci/Mekah tahun 1996. Karya sastranya (paling dominan) telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, dan Rusia. Ia pun aktif dalam berbagai organisasi sosial dan budaya, dipercaya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris.
Trikotomi Analisis Semiotik Puisi “Saling Timbang Rasa” Dienullah Rayes
Dalam buku saya berjudul Sintesemiotik: Teori dan Praktik (2023) saya menguraikan apa itu “trikotomi analisis semiotik” yang merupakan bentuk alternatif kritik puisi dari metode Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis [CDA])—pernah saya mengajar mata kuliah CDA. Metode trikotomi analisis semiotik dimulai dari analisis sintaksis, lalu analisis semantik, dan terakhir analisis pragmatik. Dalam praktiknya, pada analisis pragmatik akan pelbagai tingkat kedalaman dan keluasannya, bergantung pada kualitas puisinya. Teori yang lengkap silakan baca buku yang saya tulis di atas. Secara ringkas, sintaksis ialah tata kata, semantik tata makna, dan pragmatik tata komunikasi.
Sebagai bahan analisis, bacalah puisi di bawah ini karya Dienullah Rayes secara utuh terlebih dahulu.
Dienullah Rayes
SALING TIMBANG RASA
kata malam:
“aku tak cemburu matahari meski
dia berwajah lebih terang dari
muka gelap senyapku.”
berkata siang:
“aku pun tak pernah melihat
sebelah mata pada kening bulan
meski dia lebih bercahaya
dari dada terang panasku.”
alam semesta di bawah bulan—matahari
terbentang bumi sabar berbusana hijau berseri.
bulan, matahari, dan bumi
tata surya saling mengerat temali cinta kasih
para insan wakil Tuhan di semesta bumi
mengipas napas merajai makhluk hidup ciptaan-Mu.
Sumbawa, NTB
12 Maret 2025
Judul “Saling Timbang Rasa” secara sintaksis menggunakan kata “saling” yang bersifat resiprokal (berbalasan) tentang menimbang rasa. Judul puisi ini bersifat romantis sesungguhnya secara semantik sebab sifat berbalasan itu dan secara pragmatik kesan mesra pun tercipta dengan kata “saling” yang bersifat berbalasan itu seolah-olah kedua makhluk itu berwatak aktif satu sama lain—tak ada yang diobjekkan secara negatif atau rendah.
Simaklah bait 1 dan bait 2:
kata malam:
“aku tak cemburu matahari meski
dia berwajah lebih terang dari
muka gelap senyapku.”
berkata siang:
“aku pun tak pernah melihat
sebelah mata pada kening bulan
meski dia lebih bercahaya
dari dada terang panasku.”
Dua bait ini secara sintaksis menggunakan kalimat langsung semacam dialog dengan tanda petik yang mengapit ucapannya. Secara semantik siang dan malam bercakap-cakap dengan membandingkan matahari dan bulan dengan sosok seseorang yang disembunyikan. Percakapan kiasan (metaforis) ini tentu saja bermakna perkawinan dunia kecil (mikrokosmos) dan dunia besar (makrokosmos)—perkawinan dunia manusia dan dunia alam semesta yang luas ini. Puisi ini termasuk puisi besar dengan ide besar dalam tradisi sufistik sebab menggabungkan yang mikro dan yang makro secara alamiah. Secara pragmatik perbandingan kata-kata “lebih terang” dan “lebih bercahaya” semacam perbandingan dengan manusia tak adil sebab tentu saja matahari dan bulan tak dapat dikalahkan kualitas cahayanya, matahari lebih menyilaukan (terang) dan bulan lebih menyejukkan (cahaya).
Kini bacalah bait 3 secara lengkap.
alam semesta di bawah bulan—matahari
terbentang bumi sabar berbusana hijau berseri.
Di sini “bumi” digambarkan secara sintaksis dengan majas personifikasi (pengorangan) agar tampak seperti manusia yang “berbusana hijau berseri” di bawah terang matahari dan kemilau cahaya bulan—seakan-akan terang matahari dan cahaya bulan itu diibaratkan sesuatu yang menimpa tubuh bumi yang indah laksana usapan angin dan cahaya pada tubuh molek perempuan. Secara semantik kesan romantis yang sensual ini ialah tradisi umum dalam Sufisme. Ucapan melambung demi tercapainya gerak hati si penyair. Secara pragmatik tak ada yang disapa di sini, selain pihak pembaca secara tak langsung agar turut mengagumi keindahan alam semesta raya ini.
Bacalah bait 4, bait penutup secara utuh.
bulan, matahari, dan bumi
tata surya saling mengerat temali cinta kasih
para insan wakil Tuhan di semesta bumi
mengipas napas merajai makhluk hidup ciptaan-Mu.
Benarlah, makhluk bulan, matahari, dan bumi semua harus tunduk pada makhluk insan atau manusia—kata “insan” secara sintaksis lebih santun dan spiritual daripada kata “manusia” di sini. Secara semantik dengan adanya bulan, matahari, dan bumi manusia dapat hidup secara layak di dunia ini—sebab “wakil Tuhan” di muka bumi. Secara pragmatik, gelar wakil Tuhan inilah yang sering melenakan seluruh manusia yang lalai, hingga mereka jatuh terjerumus ke dalam jurang kerugian dan kesesatan hingga kecelakaan di dunia ini apabila tidak mengingat bahwa manusia pun sebagai “hamba Tuhan” di muka bumi.
Kesimpulan
Demikianlah puisi Dienullah Rayes, puisi dengan tema besar ini, telah mengingatkan pihak pembaca agar waspada terhadap seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang telah ditundukkan kepada manusia. Tambahan pula, peran wakil Tuhan di muka bumi haruslah pula diwaspadai karena manusia pun sebagai hamba Tuhan yang wajib taat kepada seluruh perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
Narudin Pituin
(Sastrawan, Penerjemah, dan Kritikus.